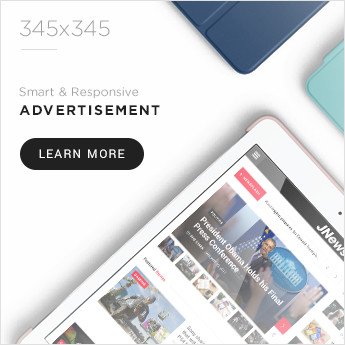Oleh: Yusuf Mars (Calon Doktor Sejarah Peradaban Islam UNUSIA)
Ada yang istimewa dari peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 kali ini. Tidak diselenggarakan di pusat kekuasaan atau gedung-gedung megah ibu kota, melainkan dari sebuah tempat yang sunyi dan sarat sejarah — Barus, Tapanuli Tengah, titik nol penyebaran Islam di Nusantara.
Di sinilah, Selasa malam (21/10/2025), Gus Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) bersama jajaran DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menapaki tanah tua peradaban. Mereka menziarahi makam Syekh Mahmud, seorang ulama besar yang dipercaya sebagai salah satu penyebar awal Islam di bumi Nusantara, jauh sebelum Islam mencapai pesisir Aceh, Jawa, dan Maluku.
Barus bukan sekadar nama geografis. Ia adalah simpul pertemuan antara jalur perdagangan internasional dan arus dakwah Islam sejak abad ke-7 Masehi. Catatan sejarah dari sumber Arab dan China menyebutkan, wilayah Barus — yang terkenal sebagai penghasil kapur barus (camphor) — telah menjadi pelabuhan kosmopolitan yang disinggahi para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia.

Menurut tradisi lokal, Syekh Mahmud (atau dikenal juga sebagai Mahmud al-Barusi) adalah salah satu figur utama dalam gelombang awal dakwah Islam di kawasan tersebut. Ia datang bukan dengan senjata, melainkan dengan ilmu, dakwah, dan teladan akhlak. Dari Barus inilah, nilai-nilai Islam tumbuh dalam harmoni dengan budaya lokal, membentuk embrio Islam Nusantara — Islam yang damai, akomodatif, dan membumi.
Ziarah Gus Imin ke makam Syekh Mahmud, dengan demikian, bukan sekadar penghormatan kepada tokoh sejarah, tetapi pengakuan terhadap akar peradaban Islam di Nusantara. Dalam pandangan Islam Nusantara, mengenal akar berarti mengenali jati diri: bahwa Islam di Indonesia tidak lahir dari ekspansi kekuasaan, melainkan dari dialog budaya dan spiritualitas.
Ziarah dalam Khazanah Islam Nusantara memiliki makna yang dalam. Ia bukan sekadar perjalanan fisik menuju makam, tetapi perjalanan batin menuju kesadaran akan asal-usul dan tujuan hidup. Dengan berziarah ke “titik nol” Islam Nusantara, Gus Imin seakan mengajak umat Islam untuk menelusuri kembali sumber cahaya — asal mula iman dan peradaban.

Dalam perspektif filosofis, “titik nol” melambangkan momen tabula rasa — kembali kepada kesucian niat, kesederhanaan dakwah, dan kemurnian perjuangan. Dari titik nol itulah peradaban dibangun, bukan dengan ambisi kekuasaan, melainkan dengan keikhlasan dan ilmu.
Pernyataan Gus Imin, “Hari Santri kali ini kita mulai dari titik nol, tempat di mana ajaran Islam pertama kali menumbuhkan peradaban,” bukan hanya kalimat simbolik. Ia adalah manifesto politik kebudayaan — ajakan untuk meneguhkan kembali posisi santri sebagai penjaga peradaban, bukan sekadar penjaga moralitas.
Dalam pidatonya tersebut, Gus Imin menegaskan bahwa sejarah bangsa ini tak bisa dilepaskan dari peran ulama dan pesantren. Dari pesantren lahir kekuatan spiritual; dari santri lahir energi moral yang menggerakkan kemerdekaan.
Ia kembali mengingatkan Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy‘ary pada 22 Oktober 1945 — fatwa monumental yang menyalakan bara perjuangan santri melawan penjajahan. “Keberanian untuk syahid mengusir penjajah itulah yang menjadi energi luar biasa bangsa ini,” ujar Gus Imin.
Momentum Hari Santri, yang kini dirayakan setiap 22 Oktober, bukan semata peringatan historis, tetapi penyalaan ulang semangat kebangsaan santri: keikhlasan, keberanian, dan tanggung jawab sosial.
Menggelar peringatan Hari Santri dimulai dari Barus adalah langkah penuh makna. Ia bukan sekadar simbol geografis, melainkan penanda arah — bahwa perjuangan santri hari ini harus kembali pada spirit awal: membangun peradaban, bukan sekadar berebut kekuasaan.
Manifesto Barus
Barus adalah tempat awal datangnya cahaya Islam; dan dari tempat ini pula, Gus Imin seolah ingin mengatakan bahwa masa depan Islam Nusantara harus dibangun dengan semangat pencerahan, bukan perpecahan.
Puncak makna ziarah itu mungkin saja dalam benak Gus Imin bisa dirangkum dalam kalimat sederhana namun penuh makna:
“Dari Barus — titik awal Islam Nusantara — kita kobarkan semangat baru: santri berdaya, Indonesia berjaya.”.
Kalimat itu bukan sekadar seruan semangat, tetapi manifesto kebangsaan. Di tengah derasnya arus globalisasi, Gus Imin mengingatkan bahwa kekuatan bangsa ini salah satunya bertumpu pada jiwa santri: religius, berilmu, berkarakter, dan berkhidmat untuk kemanusiaan.
Dari titik nol Islam Nusantara, Gus Imin mengajak bangsa ini untuk kembali kepada sumber cahaya: iman, ilmu, dan pengabdian. Karena sejatinya, menjadi santri bukan soal status, tetapi kesadaran — bahwa hidup adalah perjuangan untuk menyalakan kebaikan.