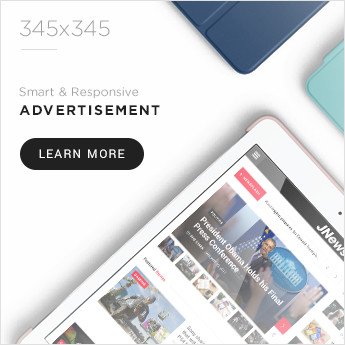Oleh Yusuf Mars
Di tengah kegaduhan dinamika Nahdlatul Ulama (NU) mutakhir, nama KH. Imam Jazuli muncul sebagai suara yang berbeda—jernih, berani, dan tidak tersandera kemapanan struktural. Ia bukan kiai panggung, bukan pula elite birokrasi organisasi. Ia hadir dari pinggiran: dari pesantren, dari tirakat, dari kesunyian intelektual yang justru melahirkan kritik tajam terhadap arah PBNU hari ini.
Saya pernah menulis tentang sosok KH. Imam Jazuli dengan judul: “Dari Kaki Gunung Ciremai, KH. Imam Jazuli Cetak Generasi NU Berkaliber Internasional”. Yaa..kiprahnya di dunia Pendidikan memang melesat.
Penampilannya sederhana—sarung dan kaos oblong putih—namun visinya jauh melampaui kebanyakan elite organisasi. Ia memimpikan pesantren sebagai pusat peradaban: berakar kuat pada tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah, sekaligus terintegrasi dengan sistem pendidikan global kelas dunia.
Saya mengenalnya bukan dari mimbar resmi NU, melainkan dari ruang diskusi yang lebih jujur dan terbuka: grup WhatsApp. Di sana, perdebatan soal NU, politik kebangsaan, hingga masa depan umat sering berlangsung keras. Dalam situasi seperti itu, tulisan KH. Imam Jazuli selalu tampil berbeda—argumentatif, sistematis, dan bernas. Kritiknya tajam, tetapi tidak emosional. Tegas, namun tetap beradab.
Intelektual Pesantren yang Membaca Zaman
Latar belakang akademiknya—Ushuluddin, Aqidah dan Filsafat, Universitas Al-Azhar Kairo—menjadikannya akrab dengan tradisi debat dan dialektika pemikiran Islam. Namun yang membuatnya menonjol bukan sekadar ijazah, melainkan konsistensi laku hidupnya. Tirakat panjang, puasa bertahun-tahun, dan wirid Dalail Khairat bukan sekadar simbol spiritual, tetapi fondasi etik dalam berpikir dan bertindak.
Pendidikan pesantrennya berlapis: Al-Ishlah Bobos, Kempek, Lirboyo, lalu berlanjut ke Kairo dan Malaysia. Kombinasi ini menjadikannya kiai yang nyantri secara tradisi sekaligus kosmopolit secara wawasan. Ia membaca kitab kuning, tetapi juga membaca geopolitik. Ia memahami fiqih ibadah, tetapi juga fiqih kekuasaan.
Visi tersebut diwujudkan dalam Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA) dan pengembangannya, Pesantren VIP BIMA, sebuah terobosan pendidikan pesantren futuristik yang memadukan manajemen modern, teknologi pendidikan global, dan ruh salafiyah NU. Di sinilah terlihat watak anti-kemapanannya: membangun sistem alternatif tanpa harus menunggu legitimasi struktur pusat.

MLB NU dan Kritik atas PBNU
Sebelum adanya dinamika dan konflik tajam di tubuh PBNU antara kubu Ketua Umum dan Kubu Syuriah (Rois Aam) yang berukjung pemakzulan Gus Yahya dan digantikan PJ Ketum PBNU, KH. Imam Jazuli bersama Gus Salam mewacanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU sebagai kritik pedas terhadap arah dan kebijakan PBNU saat itu. Bagi beliau, MLB bukan semata manuver politik, melainkan ekspresi kegelisahan struktural warga NU terhadap arah kepemimpinan PBNU yang dinilai menjauh dari khittah, basis jamaah, dan kedaulatan jam’iyah.
KH. Imam Jazuli termasuk tokoh yang terdepan mengkritisi PBNU, terutama dalam soal sentralisasi kekuasaan, orientasi politik global yang dianggap elitis, serta melemahnya posisi kiai pesantren dalam pengambilan keputusan strategis NU. Kritik itu bukan muncul dari ambisi jabatan—beliau tidak berada dalam lingkar kekuasaan PBNU—melainkan dari keprihatinan ideologis dan historis.
Riuhnya konflik PBNU belakangan ini yang memunculkan “Drama Panjang” dan berujung kedua belah pihak menyepakati muktamar dipercepat untuk menyudahi konflik, nama KH. Imam Jazuli menjadi pembicaraan kembali. Beliau lantang mengkritisinya. Kehadiran KH. Imam Jazuli ibarat hujan di tengah gurun: menyegarkan bagi banyak Nahdliyin yang merasa kehilangan saluran aspirasi.
Ia mengingatkan bahwa NU besar bukan karena diplomasi global semata, tetapi karena akar pesantren, kiai kampung, dan santri. Bahwa politik NU seharusnya menjadi sarana dakwah dan kedaulatan umat, bukan sekadar simbol prestise internasional. Sejarah Walisongo, sebagaimana sering ia sampaikan, menunjukkan bahwa dakwah dan kekuasaan harus berjalan seimbang—berbasis nilai, bukan sekadar pengaruh.
Tirakat sebagai Etika Perlawanan
Yang menarik, kritik KH. Imam Jazuli tidak lahir dari retorika kosong. Ia ditopang oleh laku spiritual yang panjang. Tirakat baginya adalah etika perlawanan. Jalan sunyi yang menjauhkan kritik dari kepentingan pragmatis. Ia tidak membangun popularitas, tidak mengejar sorotan media, tetapi konsisten mendidik santri dan menyiapkan generasi NU yang melek kitab, melek teknologi, dan melek politik.
Di bawah kepemimpinannya, BIMA telah mengirim alumni ke Mesir, Maroko, Tunisia, Turki, hingga Eropa. Pendidikan baginya adalah jalan membangun peradaban—sebuah gagasan yang sejalan dengan pendidikan transformatif: santri sebagai subjek perubahan, bukan objek doktrin.
KH. Imam Jazuli adalah kombinasi langka: intelektual, spiritualis, organisator, dan pendidik. Ia mengkritik PBNU bukan karena benci NU, tetapi justru karena cinta yang dalam pada jam’iyah ini. Ia berdiri di luar kemapanan, tetapi sepenuhnya berada di dalam tradisi NU.
Dari pesantren di kaki Gunung Ciremai, ia mengirim pesan penting: bahwa perubahan besar sering kali tidak lahir dari pusat kekuasaan, melainkan dari pinggiran yang jujur, berani, dan berakar. Dalam dirinya, pesantren bukan sekadar lembaga, melainkan basis perlawanan etik dan pusat pembaruan peradaban.
Dan mungkin, di tengah kebingungan arah NU hari ini, suara-suara seperti KH. Imam Jazuli inilah yang paling layak didengar.
Yusuf Mars, adalah Direktur Lembaga Kajian Strategis Islam Nusantara (LKSIN), Mahasiswa Doktoral Sejarah Peradaban Islam UNUSIA, dan Founder @Padasukatv.