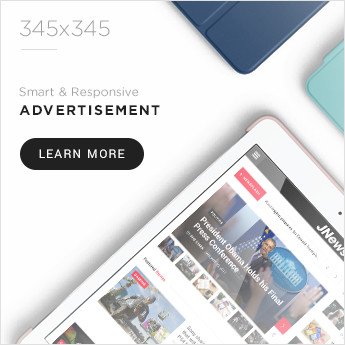Oleh: Yusuf Mars (Calon Doktor Sejarah Peradaban Islam UNUSIA)
Ketika adzan berkumandang di tengah tabuhan gamelan, tahlil bergema di antara aroma kemenyan, dan santri mengaji kitab kuning sambil membantu petani menanam padi — sebagian orang mungkin tergoda menyebutnya sinkretisme. Tapi sejatinya, di situlah Islam Nusantara menemukan wajah peradabannya: Islam yang hidup dalam kebudayaan, bukan di luar kebudayaan.
Islam Nusantara bukanlah agama yang datang untuk menggusur, tapi untuk menyuburkan. Ia tumbuh bukan lewat pedang, melainkan melalui perniagaan, perkawinan, dan persahabatan. Para wali, sejak abad ke-15, tidak meruntuhkan candi, melainkan menafsirkan ulang maknanya. Sunan Kalijaga tidak melarang wayang, ia menjadikannya medium dakwah. Sunan Bonang tidak menghapus tembang Jawa, tapi mengisinya dengan zikir. Itulah peradaban Islam yang lembut tapi mengakar, teduh tapi tangguh.
Dalam sejarah panjang Nusantara, pesantren menjadi bukti paling nyata dari daya hidup Islam sebagai peradaban. Di sana, agama tidak hanya diajarkan sebagai dogma, tapi dijalani sebagai cara hidup. Pesantren lahir dari masyarakat, tumbuh bersama rakyat, dan berakar di tanah budaya lokal.
Dari pesantren lahir ulama-ulama besar yang bukan hanya ahli agama, tetapi juga pemikir sosial dan politik. KH. Hasyim Asy‘ari mendirikan Nahdlatul Ulama untuk meneguhkan Islam yang membela bangsa. KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk menjadikan Islam sebagai pendorong kemajuan. KH. Sahal Mahfudz menulis tentang fiqh sosial, agar hukum Islam tidak kering dari realitas rakyat kecil.
Pesantren menjadi laboratorium peradaban: tempat ilmu, adab, dan kebersamaan tumbuh bersama. Dalam dunia yang makin pragmatis, pesantren adalah benteng moral yang menegaskan bahwa pengetahuan tanpa akhlak hanyalah kesombongan intelektual.
Ciri khas Islam Nusantara adalah keramahannya. Ketika di beberapa belahan dunia Islam tampil dengan wajah tegang dan ideologis, Islam di Indonesia justru menampilkan wajah yang teduh, santun, dan penuh empati. Islam yang diajarkan oleh para ulama Nusantara bukanlah Islam yang mengutuk budaya, melainkan Islam yang menyucikan makna di balik budaya.

Itulah mengapa di Nusantara, pengajian bisa digelar di balai desa, zikir dilakukan bersama warga lintas agama, dan kiai tetap dihormati bukan karena gelarnya, tetapi karena akhlaknya. Dalam tradisi kita, adab lebih tinggi daripada ilmu, dan kasih sayang lebih utama daripada perdebatan.
Peradaban Islam Nusantara tidak hanya hidup dalam ritual, tetapi juga dalam khazanah intelektual. Dari Aceh, Syekh Nuruddin ar-Raniri dan Abdurrauf as-Singkili menulis karya-karya tasawuf yang dikaji di seluruh dunia Melayu. Dari Banten, Syekh Nawawi al-Bantani menjadi guru besar di Mekkah dan menulis ratusan kitab dalam bahasa Arab. Dari Banjar, Syekh Arsyad al-Banjari menulis Sabilal Muhtadin, kitab hukum Islam yang masih digunakan hingga kini.
Ulama-ulama ini tidak sekadar menyalin ilmu dari Timur Tengah, tetapi menafsirkan Islam sesuai dengan realitas sosial Nusantara. Di tangan mereka, Islam bukan hanya ajaran langit, tetapi juga panduan untuk membangun bumi. Itulah kekuatan epistemologis Islam Nusantara: berpikir global, bertindak lokal.
Di tangan para ulama Nusantara, Islam bukan hanya ajaran langit, tetapi panduan untuk membangun bumi. Inilah kekuatan epistemologis Islam Nusantara: berpikir global, bertindak lokal.
Dan hari ini, ketika dunia diguncang oleh kebencian atas nama agama, Islam Nusantara hadir bukan sebagai nostalgia masa lalu, tetapi sebagai tawaran masa depan — peradaban yang menjahit iman dengan kearifan, dan pengetahuan dengan kasih sayang.