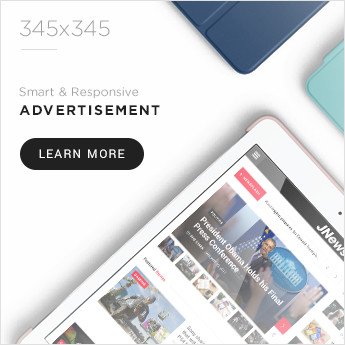Oleh Yusuf Mars
Wacana duet KH Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam PBNU dan KH Said Aqil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU mencuat di tengah ikhtiar Nahdlatul Ulama keluar dari konflik internal yang telah menguras energi organisasi. Meski belum menjadi keputusan resmi, wacana ini layak dibaca bukan sekadar sebagai kompromi elite, melainkan sebagai opsi serius untuk menata ulang arah NU di abad kedua
Konflik PBNU memberi pelajaran penting: NU tidak cukup dipimpin oleh figur yang kuat secara struktural atau administratif semata. NU membutuhkan kepemimpinan yang memiliki otoritas moral, legitimasi keulamaan, serta kemampuan merangkul lintas faksi dan generasi. Di titik inilah relevansi duet ini mulai menemukan pijakannya.
KH Ma’ruf Amin membawa modal otoritas keulamaan yang nyaris tanpa tanding. Pengalamannya sebagai Rais Aam PBNU, Ketua Umum MUI, hingga Wakil Presiden RI membentuk karakter kepemimpinan yang matang, sabar, dan cenderung meneduhkan. Ia terbiasa menjadi penentu terakhir dalam situasi pelik, bukan aktor yang memperuncing konflik.
Keputusan Kiai Ma’ruf untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Syura PKB dan Ketua Wantim MUI mempertegas satu pesan penting: menjaga marwah dan jarak Rais Aam dari politik praktis. Bagi NU, ini krusial. Rais Aam bukan sekadar posisi struktural, melainkan simbol kebijaksanaan kolektif, pengayom jam’iyah, dan penjamin adab organisasi.
Sementara itu, KH Said Aqil Siroj menawarkan kapasitas manajerial, jejaring global, dan pengalaman organisatoris yang teruji. Sepuluh tahun memimpin PBNU membuatnya memahami NU bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai kekuatan sosial-budaya dan geopolitik. Di bawah kepemimpinannya, NU tampil lebih percaya diri di panggung nasional dan internasional sebagai representasi Islam moderat, inklusif, dan berpengaruh.
Jika Kiai Ma’ruf adalah jangkar moral dan simbol persatuan, maka Kiai Said adalah mesin penggerak organisasi. Yang satu menenangkan dan mengislahkan, yang lain mengakselerasi dan mengeksekusi.
Duet ini bukan sekadar pembagian peran, melainkan potensi sinergi strategis: stabilitas di pucuk syuriah dan daya dorong kuat di tanfidziyah.
Dalam konteks NU abad kedua, kombinasi ini berpotensi membawa NU bukan hanya pulih dari konflik, tetapi melesat—mengonsolidasikan internal, memperkuat peran global, sekaligus menyiapkan regenerasi kepemimpinan yang lebih tertata.
Duet ini dapat menjadi jembatan transisi: meredam ketegangan hari ini sambil menyiapkan NU untuk fase kepemimpinan berikutnya.
Namun, perlu ditegaskan: figur besar tidak otomatis menang. Dalam tradisi NU, penentu akhir tetap berada di tangan muktamirin. Mereka membawa mandat cabang dan wilayah, dengan pertimbangan yang sering kali lebih pragmatis: keseimbangan internal, aspirasi daerah, serta kebutuhan regenerasi.
Karena itu, wacana duet Kiai Ma’ruf–Kiai Said hanya akan menemukan bentuk nyata jika mampu meyakinkan muktamirin bahwa pasangan ini bukan nostalgia masa lalu, melainkan solusi realistis untuk masa transisi NU. Tanpa dukungan akar struktural, duet ini akan berhenti sebagai diskursus elite.
Pada akhirnya, perdebatan tentang duet ini bukan semata soal siapa menjadi Rais Aam dan siapa menjadi Ketua Umum PBNU. Ini adalah ujian kedewasaan NU dalam mengelola perbedaan dan ego kekuasaan. NU di abad kedua tidak kekurangan tokoh. Yang diuji justru kemampuannya menempatkan persatuan di atas ambisi. Jika gagal, siapa pun yang terpilih, konflik hanya akan berganti wajah saja.
Yusuf Mars
CEO @PadasukaTV
CEO Lembaga Kajian Strategis Islam Nusantara dan Asia Tenggara (LEKSINAT)
Mahasiswa Doktoral Sejarah Peradaban Islam UNUSIA